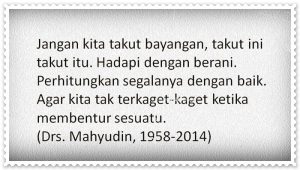Catatan Rabu, 22 Oktober 2014, 22.00 WIB, Bandar Lampung.
“Jangan kita takut bayangan, takut ini takut itu. Hadapi dengan berani. Perhitungkan segalanya dengan baik. Agar kita tak terkaget-kaget ketika membentur sesuatu.”
Kira-kira begitulah pesan papa beberapa tahun lalu, yang saya jadikan pegangan saat menemani papa mengantri giliran operasi. Saya bukan tidak khawatir terhadap kondisi papa. Tapi, ya, itu tadi, saya ingat pesan papa agar tidak takut dengan bayangan. Pokoknya berjuang semaksimal mungkin. Tentang hasilnya, itu urusan nanti. Kewajiban kita berusaha, Allah yang menentukan. Maka tidak ada pilihan lain kecuali harus optimis karena inilah usaha paling maksimal yang mungkin dilakukan saat ini. Ditambah lagi, saya sedang menemani lelaki yang setahu saya keseluruhan hidupnya dipenuhi optimisme: papa.
Di ruang tempat menunggu operasi ini saya menemani papa sendirian. Dokter memperkenankan anggota keluarga yang lain menunggu di depan ruang operasi. Saya berbisik ke papa, “Pa, sekarang kita menunggu giliran operasi. Abang di sini menemani papa.” Lalu saya menyebutkan satu per satu anggota keluarga yang menunggu di luar. “Semua berdoa untuk papa. Kita berjuang bersama untuk kesembuhan papa, ya,” tambah saya.
Saya tahu papa tidak akan memberi respons. Tapi saya yakin, papa mendengar saya. Sesekali saya bisikkan tentang Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya juga bicara tentang keikhlasan, “Ikhlaskan semuanya, ya, Pa. Ikhlaskan.” Sebenarnya saya tidak punya alasan kuat untuk bicara tentang keikhlasan. Tapi, entah kenapa kalimat itu terucap juga.
Saya pandangi wajah papa. Saya semakin mendekat, sampai jarak antara wajah papa dan saya hanya sekitar satu setengah jengkal. Ketika itulah saya melihat mata papa perlahan-lahan terbuka… Deg! Saya langsung meminta perawat untuk memeriksa papa.
Dada papa ditekan berulang kali untuk memancing detak jantungnya. Alat bantu pernapasan dipasang di mulut –tadinya di hidung. Setelah beberapa menit dan berulang kali mencoba, seorang dokter berkata, “Sudah, Mas, ikhlaskan saja.”
Agak kaget saya mendengarnya, tapi saya belum mau menyerah. “Berapa menit waktu tersisa sampai saya harus benar-benar mengikhlaskan papa saya? Bisakah kita memaksimalkan waktu yang tersisa?”
Dokter itu seperti ingin menyampaikan sesuatu ketika dokter yang lain bilang, “Ok, kita coba.”
Tim dokter dan perawat itu bekerja lagi. Mereka menekan dada papa berulang kali untuk memancing detak jantungnya. Ada sesuatu yang disuntikkan ke tangan papa. Saya merunduk, mendekat ke telinga papa. Berulang kali tubuh papa terguncang, berulang kali juga saya bisikkan ke papa, “Pa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah sayang sama papa. Allah kasih kesembuhan untuk papa. Allah, Pa. Allah… Allah… Allah… Allah… Allah….”
Setelah beberapa menit, dokter yang sama memutus bisikan saya, “Sudah, Mas, ikhlaskan.”
Saya menegakkan tubuh. “Sudah tidak ada yang bisa kita lakukan?”
“Iya, Mas. Kita sudah pacu jantungnya. Tidak ada reaksi.”
“Di monitor juga tidak terdeteksi?” Saya menunjuk ke monitor, mencari tanda kehidupan.
“Iya. Tidak ada gelombang yang terdeteksi.”
Saya berpaling ke dokter yang lain, berharap ada pendapat yang berbeda, “Nadinya juga tidak terasa?”
“Iya, Mas. Tadi kita juga sudah suntikkan andrenalin. Tidak ada reaksi.”
“Retinanya juga tidak ada reaksi?” Saya tidak benar-benar mengerti tentang apa yang saya tanyakan. Pokoknya saya bertanya saja.
“Tidak ada, Mas.”
Saya masih berpikir untuk menanyakan hal-hal lain yang mengindikasikan kehidupan seseorang. Bahkan, saya ingin mengajak tim doker dan perawat berusaha lagi, lagi, dan lagi. Namun, saya mendengar seorang perawat berbisik ke dokter, mengabarkan bahwa ada pasien lain yang sedang mengalami pendarahan. Maka saya tidak jadi bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, perjuangan papa sudah selesai. Sekarang ada pasien lain yang membutuhkan pertolongan dokter. Saya pikir, lebih baik dokter itu segera menolong pasien tersebut.
Ragu-ragu saya mengajukan pertanyan penutup, “Jadi… papa saya sudah tidak ada?”
Saya tahu bahwa saya akan sedih mendengar jawaban atas pertanyaan itu. Tapi bagaimana lagi, saya ingin mendengar sejelas-jelasnya. Dan tim dokter lebih tahu daripada saya tentang hal ini.
“Iya,” dokter itu mengangguk.
“Innalillahi wainnailaihi roji’un”. Siap tidak siap, saya harus menerima bahwa papa sudah kembali menghadap Allah.
Saya sedih, tapi saya merasa tidak memiliki banyak waktu untuk bersedih. Saya ingin segera menegarkan diri karena itulah yang sering diulang oleh papa, “Anak-anak papa harus tegar menghadapi apapun.” Atau setidak-tidaknya, saya harus mewakili papa menyampaikan rasa terima kasihnya yang tak sempat terucap.
“Tim dokter dan perawat, terima kasih telah berusaha untuk kesembuhan papa saya. Kita sudah berjuang, tapi ini memang takdir Allah. Tolong doakan papa saya,” kata saya, akhirnya. Saya tahu tak ada yang perlu dibahas lagi. Semakin cepat saya menutup percakapan ini, semakin cepat juga mereka bisa menolong orang lain.
Tim dokter dan perawat itu mengangguk-angguk sambil menunduk. Kemudian mereka pergi, meninggalkan saya yang memandangi wajah papa. Selesai perjuangan kita, Pa…
Dalam posisi berdiri, saya bersandar ke tembok. Saya tadahkan tangan. Saya memohon. Ya, Allah, telah Engkau panggil papa untuk kembali. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, sayangi papaku, kasihi papaku. Beri tempat yang nyaman, yang menyenangkan, yang indah, yang terbaik untuk papa….
Saya merasa mata saya basah seperti sehabis menguap. Saya mengerjap-ngerjapkan mata agar air mata saya keluar semuanya. Saya pikir, kalau mau menangis deras, menangislah sekarang. Sebentar lagi saya akan melangkah keluar, menyampaikan kabar duka ini ke keluarga yang menunggu di luar. Jangan sampai saya menyampaikan kabar sambil berlinang air mata. Bisa tambah panik semuanya. Tapi, ternyata tidak ada lagi air mata yang tumpah. Maka saya menutup doa saya.
Saya bersiap melangkah keluar. Sekali lagi saya merunduk, saya berbisik di telinga papa, “Papa sayang, kita telah berjuang. Kita terima takdir Allah. Papa sayang, selamat jalan….”
***
Sebulan berlalu dan saya masih belum benar-benar berani meraba isi hati saya. Kalau tidak menyadar-nyadarkan diri, mungkin saya sulit percaya bahwa semuanya telah terjadi. Semua berlalu begitu cepat dan yang tinggal hanyalah kenangan.
Tepat benar Avanged Sevenfold menggambarkan rasa kehilangan lewat “So Far Away”:
Place in time, always on my mind /
And the light you left remains but it’s so hard to stay /
When I have so much to say and you’re so far away
Sebulan berlalu dan saya masih belum benar-benar berani meraba isi hati saya. Mungkin ini memang cara Tuhan untuk membuat saya tidak terlalu merasa terpukul – saya sendiri punya keyakinan bahwa waktu akan menyembuhkan luka. Saya hampir tidak percaya bahwa saya belum mandi air mata. Kadang saya berpikir, mestinya ada banjir air mata. Dulu saya terisak-isak saat teman seangkatan kuliah “pergi” mendahului saya. Kalau kehilangan teman membuat saya meneteskan air mata sebegitunya, kenapa sekarang tidak? Entahlah. Yang jelas, air mata memang bukan suatu keharusan, tapi doa merupakan sebuah kewajiban. Masih banyak kata cinta yang ingin terucap, tapi saya sadar itu semua sebaiknya diubah menjadi doa.
Ya Allah Yang Maha Kuasa, dulu papa mengajariku memohon kepada-Mu, “Kita minta ke Yang Kuasa, kalau Yang Kuasa sudah berkehendak, semuanya bisa terjadi, ada saja jalannya.” Sepotong ajaran yang terus diulang itu menancap kuat di hatiku. Kini keyakinan itu kupakai untuk mendoakannya: Ya Ghofuur, ampunilah segala dosa papaku. Ya Arrahmaan, Ya Arrahiim, sayangi papaku, kasihi papaku. Ya Allah Yang Maha Kuasa, berilah tempat paling indah, paling nyaman, paling sejuk, paling damai untuk papaku. Bahagiakan papaku sampai tiba saatnya ia masuk ke dalam surga-Mu. Aamiin.